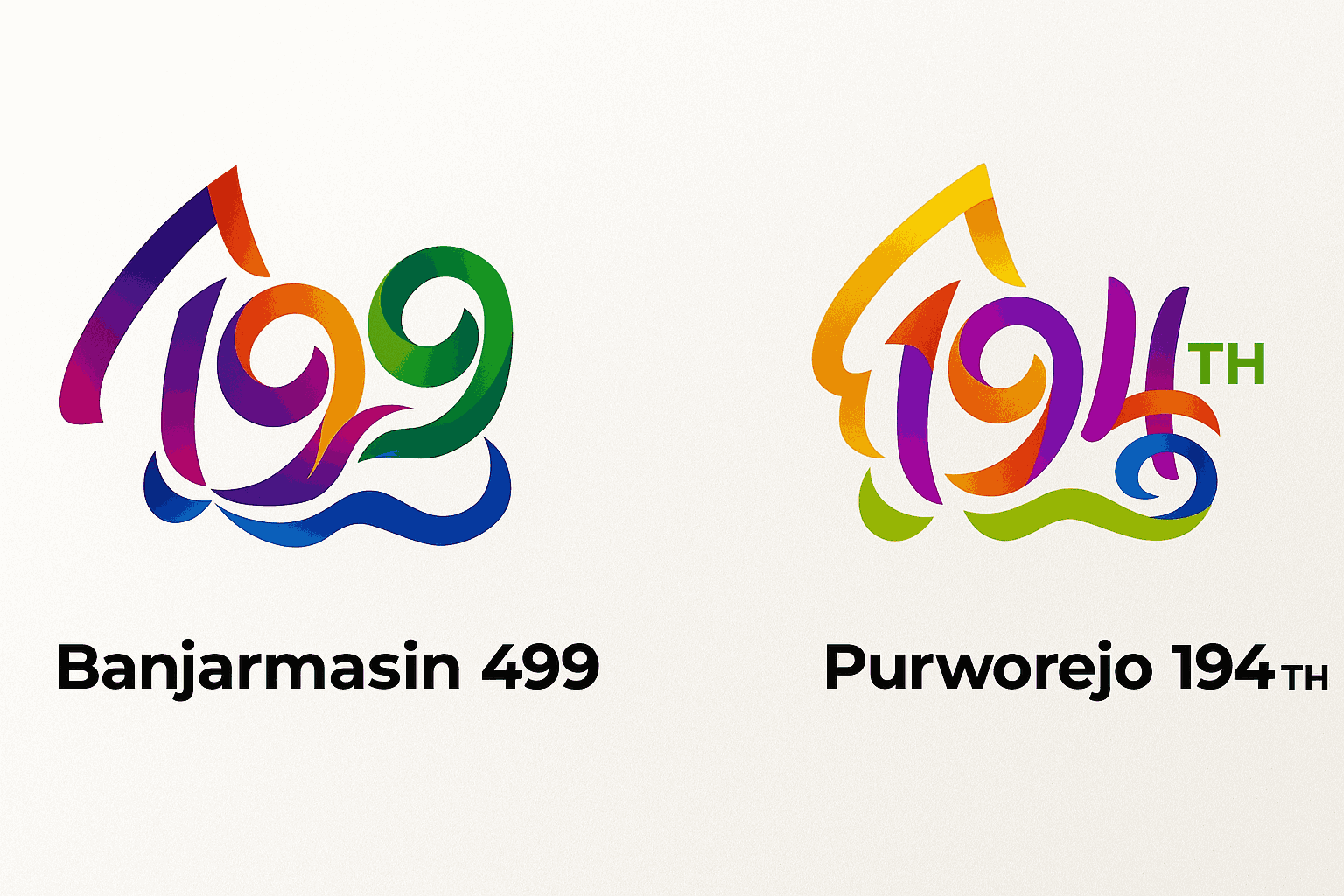- Penulis : Abdul Khair
Jika akhir-akhir ini linimasa media sosial saya dipenuhi drama serial Cina dengan alur yang mudah ditebak, maka setiap menjelang hari jadi kota, kita juga akan disuguhi “drama tahunan” yang tak kalah bisa ditebak: perdebatan soal sayembara logo hari jadi.
Ceritanya nyaris selalu sama, logo pemenang dianggap tidak representatif, kurang relevan dengan selera zaman, ide dianggap tidak orisinil, bahkan kadang dituduh sebagai “pesanan” pihak dalam, yakni pemerintah sebagai penyelenggara.
Perspektif yang saya bagikan kali ini berangkat dari pengalaman pribadi: pernah menjadi mitra penyelenggara bersama pemerintah, pernah menjadi peserta yang kalah, dan pernah menjadi juri yang menilai komunikasi visual dan orisinalitas ide. Tulisan ini adalah potongan “footage” tambahan dari drama yang seolah tak pernah menemukan akhir.
Ketidaksepahaman Komunikasi
Kesadaran pentingnya komunikasi visual dalam membranding sebuah acara mulai muncul di lembaga pemerintahan sejak 2013, salah satunya melalui sayembara logo HUT RI—informasinya tercatat di portal resmi Indonesia.go.id. Meski tidak ada data pasti kapan sayembara Hari Jadi Kota pertama kali diadakan, riuhnya lomba ini kemungkinan mengikuti tren tersebut, meski tiap kota merespons dalam waktu berbeda.
Kesadaran pemerintah untuk membangun komunikasi visual melalui logo ini bertemu dengan harapan para desainer grafis untuk mendapat apresiasi dan keterlibatan. Sayembara pun dianggap sebagai jembatan komunikasi yang tepat. Namun, di bawah permukaannya, terjadi miskonsepsi yang sampai sekarang belum menemukan titik temu:
- Pemerintah merasa membuat sayembara saja sudah cukup sebagai bentuk apresiasi. Mereka melihat ini sebagai ajang desainer menunjukkan loyalitas dan rasa memiliki terhadap kota. Harapannya, kualitas logo tetap profesional meskipun hadiah seadanya—tanpa mempertimbangkan harga logo profesional di pasaran. Pemerintah berharap narasi loyalitas menjadi alasan pemakluman.
- Desainer profesional justru melihat hadiah seadanya sebagai penurunan standar harga yang sudah mereka bangun. Akibatnya, mereka enggan ikut. Ibarat pemain bola top yang diminta main di pertandingan tarkam, ada yang mau, tapi banyak yang memilih menjaga “kaki” mereka.
- Pemerintah tetap melanjutkan sayembara untuk melibatkan masyarakat, menunjuk juri dari kalangan desainer atau seniman agar dianggap objektif. Namun, banyak juri justru kesulitan menentukan pemenang bukan karena kualitas peserta terlalu bagus, tapi karena mayoritas peserta adalah pemula. Hasilnya, pemenang sering kali masih di luar standar ideal, baik menurut dewan juri maupun pemerintah.
Di titik ini jelas terlihat: tujuan komunikasi yang diharapkan pemerintah dan desainer sudah tidak berada pada frekuensi yang sama.
Logo Hari Jadi sebagai Bagian dari City Branding Milik Masyarakat, Bukan Pemerintah
Keterbukaan pemerintah menggelar sayembara patut diapresiasi, karena belum semua kota melakukannya. Namun, perlu disadari bahwa logo Hari Jadi Kota pada akhirnya kembali kepada pemilik sesungguhnya: masyarakat.
Berbeda dengan perusahaan swasta yang bebas menentukan logo sesuai selera pemiliknya, logo Hari Jadi Kota memicu rasa kepemilikan publik. Saat pemenang diumumkan, komentar dan kritik mengalir deras. Muncul “detektif dadakan” yang mengaitkan warna dengan wali kota, bentuk dengan latar belakang juri, atau tuduhan kepentingan tertentu.
Subjektivitas ini makin kuat karena kita belum memiliki blueprint city branding yang jelas. Tanpa panduan identitas warna dan bentuk yang konsisten, setiap tahun desain berubah signifikan—menimbulkan kesan tidak konsisten dan sulit membangun ikon yang melekat. Akibatnya, tujuan jangka panjang sayembara sebagai penguatan city branding berjalan di tempat.
Kayuh Baimbai sebagai Nilai City Branding yang Terlupakan
Seperti halnya manusia dikenal bukan hanya dari wajah, tapi juga sikap, kota pun dinilai bukan hanya dari visualnya, tetapi juga dari tindakan yang diambil.
Jika selama ini kita mencoba mengapresiasi desainer melalui sayembara, mungkin sudah saatnya mencoba nilai Kayuh Baimbai, mengayuh bersama antara desainer, pemerintah, dan masyarakat. Misalnya, pemerintah mendata desainer yang layak diapresiasi, membuat standar kelayakan, lalu membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin ikut. Dari data itu dibuat mekanisme giliran tahunan atau undian acak. Yang terpilih merancang logo jauh hari, sementara yang menunggu giliran membantu memberi masukan teknis.
Pola ini mengurangi biaya, karena tidak perlu cetak selebaran atau rekrut banyak juri, dan memungkinkan hadiah lebih layak bagi satu pemenang. Pemerintah mendapat logo profesional, desainer mendapat apresiasi layak, dan masyarakat tetap terlibat melalui uji publik: logo yang sudah jadi diunggah untuk menerima masukan publik dalam waktu tertentu, lalu direvisi sesuai masukan yang relevan.
Ini mungkin bukan solusi paling sempurna, tapi layak dicoba untuk mengembalikan semangat Kayuh Baimbai. Apresiasi terhadap desainer tidak harus selalu lewat kompetisi, tapi bisa dengan merangkul mereka dalam kolaborasi yang membangun.***

Penulis merupakan seorang master program ilmu komunikasi, Ketua Kreatif Muda Indonesia (KMI) dan juga pegiat isu city branding. Tinggal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.