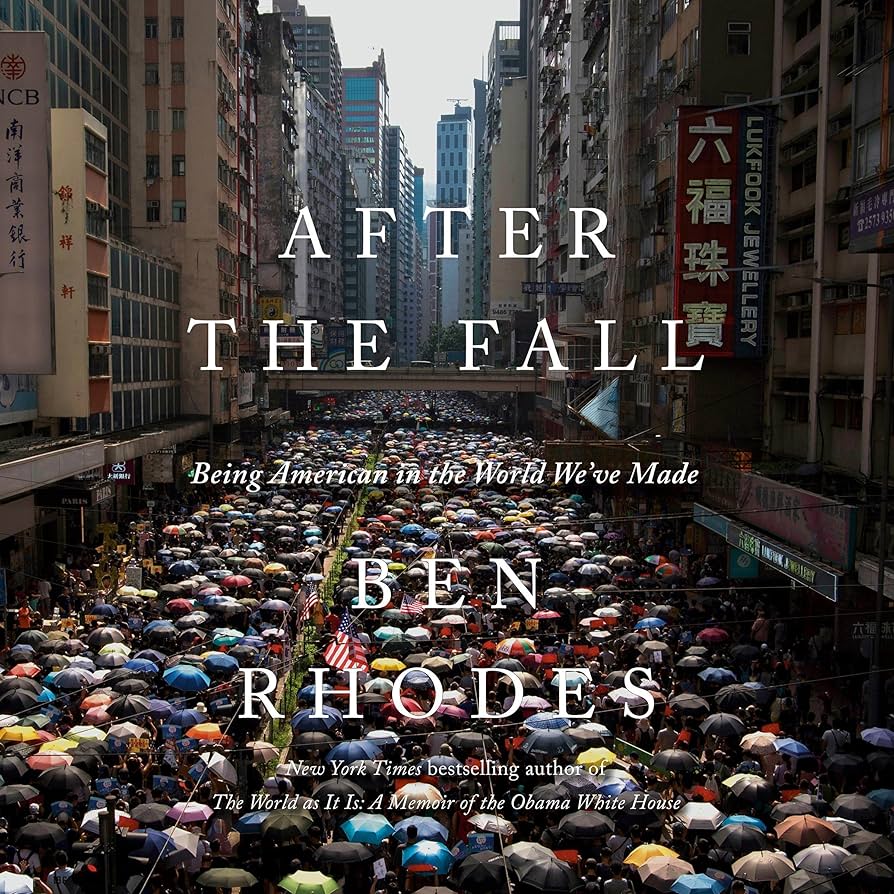Di tengah dunia yang makin gamang membedakan antara kebebasan dan ketakutan, buku After the Fall karya Ben Rhodes hadir sebagai cermin besar yang memaksa Amerika melihat bayangannya sendiri. Ia menelusuri bagaimana ilusi kemenangan pasca-Perang Dingin justru membuka jalan bagi krisis moral yang kini mengguncang demokrasi di berbagai belahan dunia.
Oleh: M Najeri Al Syahrin
Buku ini menyatakan bahwa “momen unipolar” pasca-Perang Dingin, di mana Amerika Serikat (AS) menjadi negara utama dalam tatanan internasional liberal, dibangun di atas fondasi yang cacat. Buku ini merupakan perpaduan antara memoar pribadi dan analisis geopolitik Ben Rhodes, seorang mantan penasihat kebijakan luar negeri dan penulis pidato Presiden Barack Obama, yang melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk memahami bagaimana kondisi demokrasi global berubah setelah era Perang Dingin serta memahami bagaimana posisi superpower Amerika Serikat yang terus berubah. Inti tesis dan analisis utamanya adalah Amerika tidak lagi berdiri tegak sebagai “penjaga demokrasi” melalui kebijakan luar negeri, keunggulan ekonomi, teknologi dan militer pasca-Perang Dingin. Namun AS ikut serta membentuk lingkungan global yang kemudian membalikkan diri menjadi tantangan internal bagi demokrasi dan identitas Amerika. Setelah kemenangan atas Uni Soviet dalam Perang Dingin, AS mengekspor tiga hal nilai utama pada dunia yakni pasar bebas global, dominasi teknologi dan keuangan, serta keyakinan bahwa nilai-nilai demokrasi liberal. Namun, alih-alih menghasilkan dunia yang lebih adil, globalisasi menciptakan ketimpangan ekstrem dan dislokasi sosial. Kapitalisme tanpa kendali menumbuhkan elitisme dan populisme, dua sisi mata uang yang sama. Rhodes melihat Trumpisme, Brexit, Putinisme, dan Xi-isme sebagai mutasi dari DNA global yang diciptakan AS sendiri. Dunia “bebas” yang dulu dijanjikan, kini menjadi dunia yang meniru sisi terburuk Amerika yakni polarisasi, konsumerisme, dan politik identitas.
The Authoritarian Playbook
Bab pertama dibuka dengan nada reflektif yang memadukan perjalanan pribadi dan analisis geopolitik. Ben Rhodes menulis dari posisi seorang pengamat yang baru saja meninggalkan pusat kekuasaan Amerika dan kini berkelana menelusuri tanda-tanda kemunduran demokrasi global. Ia menyadari bahwa krisis demokrasi bukan lagi isu lokal Amerika, melainkan fenomena transnasional yang berakar pada kelelahan moral, ketimpangan ekonomi, dan erosi kepercayaan terhadap institusi.
Dalam narasinya, Rhodes menggambarkan keterasingannya terhadap kondisi politik Amerika setelah naiknya Donald Trump. Ia menafsirkan perjalanannya ke berbagai negara dari Myanmar hingga Eropa Timur sebagai bentuk pencarian makna di tengah perubahan global yang membingungkan. Di Myanmar, ia menyaksikan ironi demokrasi modern melalui sosok Aung San Suu Kyi, yang dulu menjadi simbol kebebasan tetapi kemudian diam terhadap tragedi Rohingya. Bagi Rhodes, diamnya Suu Kyi bukan sekadar kegagalan moral, melainkan tanda bahwa arus nasionalisme baru telah menelan idealisme yang dulu menjanjikan kebebasan.
Perjalanan Rhodes ke Eropa memperdalam pemahamannya tentang pola otoritarianisme modern. Melalui kisah Viktor Orbán di Hungaria, ia menunjukkan bagaimana populisme kanan dapat bertransformasi menjadi sistem kekuasaan yang efisien, yakni memanipulasi media, memperkaya oligarki, dan menanamkan ketakutan terhadap “musuh bersama.” Ia menyimpulkan bahwa Orbanisme bukan penyimpangan, tetapi gejala global yang lahir dari kerapuhan sistem liberal itu sendiri, gejala yang juga tampak di Amerika. Dengan demikian, Trump dalam pandangan Rhodes bukanlah penyebab utama kemunduran, melainkan produk logis dari struktur sosial-ekonomi yang dibentuk oleh kebijakan liberal pasca-Perang Dingin.
Rhodes menolak narasi kemenangan abadi liberalisme yang pernah dielu-elukan setelah jatuhnya komunisme. Ia menunjukkan bahwa globalisasi dan kapitalisme neoliberal tidak membawa pemerataan, tetapi justru memperlebar jurang ketimpangan dan menumpulkan semangat moral demokrasi. Diplomasi yang dulu dimaknai sebagai alat kemanusiaan berubah menjadi instrumen ekonomi dan politik korporasi. Dalam pandangan Rhodes, Amerika telah kehilangan arah moralnya. Idealisme digantikan oleh kalkulasi pasar, dan pengaruhnya di dunia melemah karena lebih banyak menanam benih otoritarianisme daripada menumbuhkan kebebasan.
Melalui gaya penulisan yang realistis sekaligus analitis, Rhodes menempatkan dirinya sebagai saksi atas dunia yang dibentuk oleh negaranya sendiri. Ia menulis dengan kesadaran pahit bahwa kemunduran demokrasi bukanlah akibat kekuatan asing, melainkan refleksi dari kegagalan Amerika menjaga nilai-nilai yang dulu ia sebarkan. Ini menegaskan dua pemikiran besar bahwa krisis demokrasi global adalah akibat langsung dari ketidakadilan yang dibiarkan tumbuh di era globalisasi, dan bahwa otoritarianisme modern muncul sebagai respons terhadap kehampaan makna yang ditinggalkan oleh kapitalisme liberal. Dalam kerangka itu, After the Fall berdiri bukan sekadar sebagai catatan kejatuhan Barat, melainkan sebagai renungan tentang tanggung jawab moral terhadap dunia yang diciptakan atas nama kebebasan.
The Counterrevolution
Dalam bagian ini, Ben Rhodes menelusuri kebangkitan kembali nasionalisme Rusia sebagai tanda dari retaknya tatanan moral yang dulu dijanjikan liberalisme pasca-Perang Dingin. Ia menulis dengan gaya yang reflektif dan personal, menyatukan kenangan masa kecil, perjumpaan dengan tokoh-tokoh kontemporer, dan renungan politik menjadi satu alur naratif yang intim. Amerika, baginya, tumbuh dalam rasa kemenangan yang tak terbantahkan atas komunisme, sementara Rusia tumbuh dalam luka kolektif karena kehilangan imperium dan arah. Dari dua memori ini, Rhodes menarik pelajaran pahit bahwa ide-ide besar seperti kebebasan dan kemajuan dapat membusuk menjadi kesombongan kosong ketika kehilangan pijakan moral dan keadilan sosial.
Ia mengenang masa kecilnya ketika menjadi “anti-Rusia” dianggap bagian dari menjadi “Amerika sejati”, dan baru menyadari kemudian bahwa di sisi lain, anak-anak Rusia dibesarkan dengan keyakinan serupa, bahwa mereka adalah bangsa terbaik di dunia. Dalam sosok Alexey Navalny, Rhodes melihat generasi yang terperangkap di antara dua dunia itu, anak didik sistem Soviet yang menyaksikan ideologi negaranya runtuh dan berganti dengan kemiskinan serta rasa malu kolektif. Bagi Navalny, kebanggaan nasional berubah menjadi trauma yang kemudian dipelintir oleh rezim Putin menjadi bahan bakar bagi nasionalisme baru.
Melalui kisah Rusia, Rhodes memperlihatkan bagaimana kekuasaan otoriter modern tak lagi dibangun atas ide, melainkan atas dendam. Putin, tulisnya, memulihkan kehormatan Rusia bukan dengan membangun sesuatu yang baru, tetapi dengan menghancurkan simbol-simbol moral Barat, membuat Amerika tampak munafik di mata dunia. Di sini, Rhodes membaca Rusia sebagai pusat “kontra-revolusi global,” sebuah gerakan balik melawan liberalisme yang kehilangan makna dan arah.
Analisis Rhodes memikat karena ia memadukan lanskap besar politik dunia dengan pengalaman mikro dalam memori keluarga, pertemuan pribadi, dan bayangan masa lalu yang terus berulang. Ia menunjukkan bahwa dunia pasca-Perang Dingin tidak pernah benar-benar damai, kemenangan yang tak pernah dikaji ulang justru menanam benih kehancuran baru. Rusia dan Amerika kini saling mencerminkan dua bangsa yang sama-sama diliputi sinisme, kehilangan kepercayaan pada kebenaran, dan terus mencari kambing hitam untuk mengisi kekosongan identitas.
Dengan gaya bahasa yang lembut namun tajam, Rhodes menutup bagian ini dengan peringatan bahwa sejarah tidak selalu bergerak maju. Ia berputar, membawa manusia menyanyikan kembali lagu lama kekuasaan dan penindasan dengan nada yang berbeda namun irama yang sama. Dalam kata-katanya sendiri, seperti himne Rusia yang dihidupkan kembali oleh Putin, “lagunya tetap sama,” sebuah metafora getir tentang dunia yang tak pernah benar-benar belajar dari masa lalunya.
Putin and Obama: Two Worldviews
Dalam bagian ini, Ben Rhodes menggambarkan benturan dua kekuatan dunia yang lahir dari luka sejarah dan kehilangan arah moral. Amerika yang runtuh oleh kesombongan pasca-Perang Irak, dan Rusia yang bangkit dari trauma kekalahan dengan logika dendam. Ia menulis bukan sekadar perbandingan dua pemimpin (Bush dan Putin) melainkan dua jiwa peradaban yang sama-sama tersesat antara ilusi kekuasaan dan kehilangan makna. Amerika, yang dulu menjadikan demokrasi sebagai misi moral, berubah menjadi negara yang menggunakan idealisme itu untuk membenarkan invasi dan penyiksaan. Sementara Rusia, karena keruntuhan imperiumnya, menemukan kembali martabatnya lewat nasionalisme dan ketakutan kolektif.
Rhodes memulai kisahnya pada tahun 2004, ketika ia bekerja di Washington dan menyaksikan dari dekat bagaimana perang Irak membongkar kebusukan moral Amerika. Demokrasi dijadikan alat retorika untuk menutupi ambisi geopolitik; “pembebasan” justru melahirkan kekerasan baru. Citra tentara Amerika yang melakukan waterboarding menjadi simbol bahwa bangsa yang dulu menentang tirani kini meniru tirani itu sendiri. Di sinilah, kata Rhodes, mitos Amerika sebagai pelindung kebebasan mulai retak, dan keretakan itu diamati dengan penuh kepuasan oleh Vladimir Putin. Bagi Putin, perang Irak hanya menegaskan keyakinannya bahwa Amerika adalah imperium munafik yang mengagungkan hukum hanya saat menguntungkan dirinya.
Namun, di tengah kehancuran moral itu muncul suara lain yakni Barack Obama. Rhodes menempatkan pidato Obama dalam Konvensi Demokrat 2004 sebagai titik balik spiritual Amerika, sebuah seruan untuk mengembalikan kemanusiaan dalam politik. Obama berbicara tentang anak-anak yang bisa tidur dengan aman, warga yang dapat berbicara tanpa takut, dan solidaritas lintas ras dan kelas. Bagi Rhodes, pidato itu adalah versi paling jernih dari cita-cita Amerika, bukan bangsa penakluk, melainkan bangsa yang berusaha memperbaiki diri.
Di sisi lain dunia, hanya beberapa minggu kemudian, Putin berpidato setelah tragedi penyanderaan Beslan—dua pidato yang mencerminkan dua arah peradaban. Jika Obama berbicara tentang kekuatan yang lahir dari empati, Putin berbicara tentang kekuatan yang tumbuh dari ketakutan. Ia menyimpulkan dengan satu kalimat yang kemudian menjadi dasar politik Rusia modern: “Kita menunjukkan kelemahan, dan yang lemah akan dikalahkan.”
Kalimat itu menjadi semacam doktrin bagi Rusia pasca-Beslan. Putin membangun negaranya dengan menukar kebebasan untuk keamanan, dan pluralisme untuk martabat nasional. Ia menutup pemilihan gubernur, membungkam media, serta memperkuat kendali terhadap masyarakat sipil. Ia menjual ilusi stabilitas kepada rakyat yang haus kepastian setelah dekade penuh kekacauan. Rhodes membaca ini bukan sebagai kebetulan, tetapi sebagai refleksi dari arus besar sejarah: ketika kebebasan gagal memberi makna, kekuasaan akan mengisinya dengan rasa takut.
Dalam analisis yang jernih dan melankolis, Rhodes melihat bahwa Amerika dan Rusia akhirnya saling meniru. Amerika, dalam keangkuhannya, mengajarkan kepada dunia bahwa kekuasaan bisa dibungkus dengan bahasa moral. Rusia, dalam kebangkitannya, membalikkan pelajaran itu untuk mempermalukan gurunya. Putin menggunakan instrumen yang diciptakan dunia liberal—kapitalisme global, media sosial, dan energi—untuk melawan tatanan itu dari dalam. Disinformasi dan propaganda digital menjadi senjata paling efektif, bukan untuk meyakinkan, tetapi untuk membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada kebenaran.
Rhodes menyimpulkan bahwa dunia pasca-Perang Dingin bukanlah kisah kemenangan demokrasi, melainkan kisah tentang refleksi yang kelam. Amerika menularkan dosa-dosanya kepada musuh yang ia ciptakan; Rusia meniru kesalahan itu untuk membenarkan kekuasaannya sendiri. Keduanya kini berdiri di hadapan cermin yang sama, dua bangsa besar yang saling menuduh, namun sesungguhnya serupa dalam keretakan moral dan dahaga legitimasi. Melalui gaya naratif yang lembut namun menusuk, Rhodes mengingatkan bahwa peradaban bisa kehilangan arah bukan karena perang, melainkan karena lupa mengapa kebebasan harus dijaga.
The Chinese Dream
Dari kamar hotel di Shanghai hingga percakapan dengan aktivis di Hong Kong, ia menelusuri perubahan besar dalam tatanan global. Kapitalisme Amerika yang dulu dianggap membawa kemakmuran justru melahirkan ketimpangan dan kehilangan makna moral. Dunia yang dahulu dijanjikan sebagai ruang kebebasan kini menjadi “cermin terbalik,” tempat di mana teknologi, media sosial, dan pasar bebas berkembang pesat tanpa menumbuhkan kebebasan itu sendiri.
Cina menjadi lambang paling jelas dari transformasi ini. Dengan membuka ekonomi dan menutup ruang politik, Partai Komunis berhasil memadukan pertumbuhan ekonomi yang spektakuler dengan kendali sosial total. Nasionalisme, sensor, dan pengawasan digital menjadi alat baru untuk menggantikan ideologi lama. Rhodes menggambarkan bagaimana dunia yang dibangun Amerika—penuh citra kemajuan, inovasi, dan konsumsi—diambil alih oleh kekuatan yang lebih disiplin, efisien, dan tanpa keraguan untuk mengorbankan kebebasan individu. Sementara itu, Amerika sendiri mulai menyerupai apa yang dulu ia lawan: masyarakat yang terpolarisasi, terobsesi citra, dan kehilangan kemampuan untuk bertindak kolektif.
Dengan gaya naratif yang jujur dan introspektif, Rhodes tidak hanya mengkritik kebijakan luar negeri Amerika, tetapi juga menggugat kehilangan arah moral bangsanya. Ia menegaskan bahwa kemunduran demokrasi global bukan disebabkan oleh musuh dari luar, melainkan oleh kelalaian Amerika menjaga nilai-nilai yang dulu menjadi kekuatannya.
Who We Are: Being American
Bagian penutup After the Fall: Being American in the World We Made menempatkan Amerika di hadapan cermin sejarahnya sendiri. Rhodes menulis dengan nada getir sekaligus penuh kasih, bangsa yang dulu memproklamasikan diri sebagai simbol kebebasan kini harus mengakui bahwa keruntuhannya bukan akibat serangan musuh, melainkan buah dari keangkuhan dan kebutaan moralnya sendiri. Pandemi COVID-19 menjadi titik balik yang membuka semua lapisan luka, menyingkap sistem yang menelantarkan warganya di tengah kelimpahan, ideologi yang lebih sibuk mempertahankan dogma daripada melindungi kehidupan.
Amerika terlihat seperti negara yang kehilangan kendali atas narasi sendiri, jalanan penuh mural duka, pasukan bersenjata berpatroli di tengah masyarakat yang ketakutan, dan demonstrasi yang menyerukan agar nyawa orang kulit hitam dianggap setara. Bagi Rhodes, semua ini bukan sekadar krisis sosial, tetapi tanda bahwa bangsa tersebut sedang mencari kembali jiwanya.
Meski penuh kritik, Rhodes tidak berhenti pada keputusasaan. Ia menemukan bentuk patriotisme baru—patriotisme yang tidak menutup mata terhadap dosa sejarah, melainkan mencintai Amerika dengan keberanian untuk mengakuinya. Ia melihat perjuangan di jalanan Amerika sebagai gema perjuangan global melawan otoritarianisme di Rusia, Hongaria, dan Hong Kong. Di tengah keruntuhan tatanan lama, ia melihat kesempatan untuk membangun kembali makna kebebasan dan kesetaraan, bukan sebagai slogan, melainkan sebagai laku hidup.
Penutup
Rhodes menutup bukunya dengan keyakinan bahwa Amerika, seperti manusia yang pernah jatuh, masih memiliki kesempatan kedua. Kekuatan sejatinya tidak terletak pada superioritas ekonomi atau militer, melainkan pada kemampuannya untuk memperbaiki diri, dan menegakkan kembali martabat manusia. Ia menulis bukan sebagai mantan pejabat, tetapi sebagai warga yang belajar bahwa mencintai negaranya berarti terus menuntutnya menjadi lebih manusiawi, lebih jujur, dan lebih adil. After the Fall menjadi pengingat bahwa keagungan sejati Amerika—dan peradaban mana pun—tidak diukur dari dominasinya atas dunia, tetapi dari kemampuannya untuk belajar dari kesalahannya dan kembali menjadi kekuatan yang memanusiakan.
*Penulis merupakan Mahasiswa S3 Program Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia
dan Dosen FISIP Universitas Lambung Mangkurat